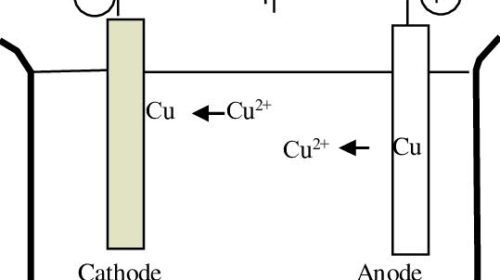Jalur Rempah: Masa Lalu dan Masa Depan Kita
Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gedung, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut
Bait pertama puisi Chairil Anwar berjudul “Senja di Pelabuhan Kecil” ini, meski secara konotatif tak hendak membicarakan ihwal soal pelabuhan, namun mampu menggambarkan apa yang terjadi di Nusantara. Sebuah bangsa yang pernah besar dan berjaya di lautan pada masa lalu, yang sayangnya kehilangan tajinya tanpa sisa.
Bagaimana tidak? Kota-kota pelabuhan di Nusantara pada abad 15-17 seperti Aceh, Banten, Demak, Makassar, Ternate, Tidore dan Sumbawa yang menjadi pusat-pusat perdagangan dunia di belahan Selatan, yang kebesarannya sejajar dengan kota-kota pelabuhan besar di utara seperti Amsterdam, Genoa, Venesia, dan Antwerp, hilang tanpa bekas seolah ditelan tsunami besar. Bangsa dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada ini, kurang dari satu abad telah berubah “memunggungi laut”, dan menjadikan daratan sebagai orientasi baru didorong oleh perubahan sejarah, yang membalik arus kebudayaan. Terpisahnya dunia maritim dari kebudayaan, yang juga turut mengubah bangsa yang sejak lama mengamini bahari, menjadi agraris.
Kita tentu bisa menunjuk kolonialisme yang dibawa Belanda sebagai biang keladi. Mereka menundukkan pelabuhan-pelabuhan besar itu dan menjadikannya sebagai bagian dari koloni mereka. “Saat kota-kota pelabuhan di pesisir dikuasai asing, pribumi bergeser ke pedalaman. Sejak itu pula kontak dengan dunia luar terputus. Putusnya kontak dengan dunia luar, bersamaan dengan putusnya keberlangsungan sebuah kebudayaan yang selama ini menjadi kuat karena semangat mencari pengetahuan dan teknologi,” mengutip Pidato Kebudayaan 2014, yang dibawakan Hilmar Farid.
Sementara itu, saat maskapai dagang VOC melakukan operasi Hongi Tochten (pelayaran hongi), mereka tidak hanya mengelilingi pulau dan menghancurkan perkebunan-perkebunan pala demi menjamin monopoli perdagangan di wilayah Maluku, namun juga merenggut ribuan nyawa dan harta benda. Tanaman serta kehidupan ekonomi orang-orang Banda beserta kebudayaan yang selama ini telah menjamin orang Maluku bisa bertahan hidup secara mandiri sebagai komunitas bahari.
Dimulailah masa-masa amnesia sejarah bagi bangsa kita. Lupa laut ternyata jauh lebih berbahaya daripada sekadar lupa daratan. Pengaruh amnesia laut ini sangat terasa saat kita berkali-kali menerjemahkan konsep Archipelagic State sebagai negara kepulauan. Padahal secara semantik kata archipelago berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu arkhi yang artinya utama dan pelagos yang artinya laut. Lautlah yang utama. Dengan demikian, archipelago harus kita baca sebagai “lautan yang ditaburi pulau-pulau” bukan sebaliknya.
Perbedaan pengertian ini tidak bisa dilihat sebagai perbedaan semantik semata, tapi merupakan perbedaan cara pandang, dan dengan demikian adalah bentuk pergeseran budaya. Dengan menyebut negara kepulauan, maka laut dilihat sebagai masalah, sebagai penghalang, bukan lagi sebagai fokus utama maupun sebagai potensi serta ruang sosial serta kultural yang utuh yang memungkinkan kita membangun kehidupan baru, budaya baru. Sebaliknya, dengan sebutan negara kelautan, maka orientasi arah pandang kita mengacu pada laut sebagai potensi, sebagai ruang kehidupan baru. Kekeliruan penerjemahan tak dinyana memiliki implikasi yang sangat besar.
Dalam khazanah sastra kita, bisa ditemukan beberapa petunjuk perlawanan sia-sia terhadap amnesia laut tersebut. Laut adalah “tujuan biru” menurut Chairil Anwar. Menurutnya, biru adalah warna untuk menggambarkan sesuatu yang jauh. Seperti halnya gunung yang tinggi dan langit yang luas, maka biru laut memberi makna buat sebuah ruang tak terjangkau. Demikianlah, sebelum peralatan navigasi modern ditemukan, maka batas laut hanyalah ombak yang tak terhitung, langit yang tak berujung dan gemintang yang memenuhi cakrawala. Kita tak pernah tahu apa yang ada di seberang sana, selain biru: tujuan biru, katanya lagi.
Sajak “Menuju ke Laut” Sutan Takdir Alisjahbana secara metaforis menggambarkan sebuah perjalanan meninggalkan masa lalu. Sajak yang dimulai dengan frasa “kami telah meninggalkan engkau” itu tampaknya ingin memperlihatkan bahwa laut adalah tujuan baru di masa depan yang harus segera ditempuh dengan meninggalkan hidup di “tenang tasik yang tiada beriak”. Sebuah ketentraman hidup dalam pelukan adat-istiadat yang meninabobokan, berganti dengan kehidupan baru yang lebih dinamis di laut sana. Meminjam Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir, Laut menjelma masa depan, meninggalkan darat dan teluk yang tenang jauh tertinggal di belakang.
Kita juga patut merenungkan amsal dari filsuf Friedrich W. Nietzsche berjudul Dalam Horison Ketidakterbatasan, “Kita telah meninggalkan daratan dan sudah menuju kapal! Kita sudah membakar jembatan di belakang kita—dan lagi, kita juga sudah menghanguskan daratan di belakang kita! Dan kini, hati-hatilah kau kapal mungil! Samudera raya mengelilingimu: memang benar, dia tidak senantiasa mengaum, dan kadang-kadang dia tampak lembut bagaikan sutra, emas, dan mimpi yang indah. Namun akan tiba waktunya, bila kau ingin tahu, bahwa dia tidak terbatas.” Nietzsche menggambarkan laut sebagai masa depan penuh kemungkinan. Meski tak selalu menjanjikan ketenangan dan kelembutan bagai sutra, laut adalah dunia baru kita. Nyatalah, laut adalah masa depan. Cakrawala harapan dan kebebasan tanpa batas. Keluasan tanpa akhir, kedalaman tak terjelajahi. Demikianlah para filsuf dan penyair menjadikan laut metafora bagi sebuah dunia masa depan, wujud segala peluang dan kemungkinan. Sebuah antitesa dari daratan dan teluk yang digambarkan sebagai ketentraman purba yang kadaluarsa, yang membenam dan menjerat kaki hingga menghalangi kita beranjak menuju dunia baru yang lebih dinamis dan menjanjikan. Dan laut, sekali lagi, menjelma sebuah harapan kehidupan yang baru, yang segera melemparkan daratan ke masa silam.
Jika laut adalah masa depan dan daratan adalah masa lalu, mengapa dalam kehidupan berbangsa kita hari ini yang terjadi sebaliknya? Sepertinya hanya sedikit yang mengetahui cerita tentang keberanian pelaut Bugis menjelajahi setengah wilayah dunia–dari Paskah hingga Madagaskar–dengan perahu-perahu bercadik. Tahu bahwa nenek moyang kita berasal dari dua kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menjadi penguasa laut.
Tak cuma itu. Bahkan yang terlintas di kepala sebagian orang kota tentang laut adalah gambaran sebuah keterbelakangan. Wujud ketertinggalan dibanding kehidupan modern lainnya. Maka bayangan kita tentang laut segera disergap oleh potret kekumuhan dan kemiskinan permukiman nelayan. Yang lebih menyedihkan, sebagian kita terjangkit virus orientalisme saat memandang kearifan masyarakat bahari seperti di Mandar dan suku Bajo sebagai bentuk kehidupan primitif. Laut bisa jadi hanya sebatas sejarah. Lalu apa manfaat kehebatan sejarah laut buat bangsa? Kebanggaan yang bisa dikenang? Menurut Michel Foucault, manusia modern hingga abad ke-20 adalah manusia yang terobsesi dengan sejarah. Obsesi mereka pada sejarah (waktu), telah membawa pada kecenderungan meremehkan peran penting yang lain. Kita saksikan filsafat dan pengetahuan modern dipenuhi oleh gagasan besar tentang “progress”. Mulai dari Hegel tentang proses evolusi rasio manusia, proses keunggulan rasio melawan kekuatan-kekuatan irasional (Comte), proses evolusi organisme (Darwin), proses lahir, tumbuh dan runtuhnya peradaban (Spengler & Toynbee), hingga perjuangan kelas (Marx), menunjukkan idea of progress mewarnai pemikiran khas zaman itu.
Namun di pertengahan abad muncul perubahan signifikan cara memandang sejarah. Bersamaan makin problematisnya objektivitas di area epistemologis, dipersoalkan pula konsep objektivitas sejarah. Meski de facto bermain di wilayah rekonstruksi atau sekadar mengiru masa lalu, sejarah bergeser menuju wilayah konstruksi yang produktif. Lemah dalam klaim objektivitas, membuat sejarah menjadi kegiatan “mencipta masa lalu”, meski berlandaskan teks dan bukti. Sebuah proses konstruksi naratif bersifat intertekstual, tafsir atas tafsir yang tidak sederhana, dan pemilihan peristiwa dan tokoh yang dianggap bernilai sangat ditentukan oleh visi teoritis dan kepentingan tertentu. Sejarah kini menjadi kegiatan menafsir, menata, dan mengelola masa lalu.
Beruntung, kecenderungan abad 21 membawa kita keluar dari telikungan ideologis, metafisika yang abstrak, dan positivisme ilmiah. Kita bergerak menuju pengalaman yang lebih konkret, dinamis, dan kompleks. Itu sebabnya kita perlu mendengar petuah pemikir posmodern Edward Soja dalam buku Postmodern Geographies yang mengatakan, “untuk manusia modern kesadaran ruang (geografis) sama pentingnya dengan kesadaran waktu (sejarah)”. Mengikuti anjuran Soja, kita harus menangkap maksudnya dengan jelas, yaitu: mari kita lihat manfaat ruang geografis selain manfaat sejarahnya. Soja, menghadirkan Imajinasi Geografis melengkapi imajinasi lama, Imajinasi Historis. Kita perlu melihat sesuatu yang lebih nyata yaitu lingkungan geografis di mana kita hidup dari pada terus-menerus bersandar pada kenangan dan kisah-kisah besar masa lalu.
Sejarah harus digunakan secara kreatif dan kontekstual untuk kebutuhan zaman. Sejarah harus digunakan untuk memaksimalkan proses penguasaan ruang geografis. Sejarah harus membuat kita sadar bahwa kita pernah menjadi bangsa yang mampu memaksimalkan penguasan ruang geografis.
Jika manfaat geografis menjadi orientasi masa depan, mari kita tinggalkan ilmu sejarah sejenak dan kita masuk ke wilayah disiplin geografi, khususnya bidang yang disebut antropogeografi yang kelak lebih populer disebut Geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kesadaran akan konsepsi ruang dalam kehidupan politik, tentang pentingnya memanfaatkan ruang geografis. Pakar geopolitik Andrew Gyorgy mengatakan, “setiap bangsa memiliki konsepsi ruang, yakni ide tentang batas-batas kekuasaan teritorialnya masing-masing. Hancurnya sebuah bangsa merupakan hasil dari menurun dan diabaikannya konsepsi tentang ruang itu.
Geografi selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Geografi membentuk identitas, karakter, dan sejarah negara-bangsa (nation-states); geografi juga membantu–sekaligus menghalang–kemajuan ekonomis, sosial, dan politik; geografi juga berperan penting dalam hubungan internasional. Sementara geopolitik merupakan studi mengenai pengaruh faktor geografis terhadap perilaku negara, yakni bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan kondisi fisik menentukan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dan menentukan posisinya dalam hierarki negara
Wilayah nasional suatu negara adalah modal dasar kodrati yang harus didayagunakan untuk mendukung kehidupan bangsa tersebut. Kemajuan teknologi, berkurangnya sumber daya alam dan pertambahan penduduk telah menjadikan ruang dunia relatif semakin sempit. Itu sebabnya setiap bangsa harus berikhtiar menjadikan wilayah nasionalnya masing-masing sebagai ruang hidup yang mampu mendukung kebutuhan bangsanya seoptimal mungkin. Demikian pula laut. Laut bisa menjadi pilihan berikutnya, laut bisa menjadi sumber kehidupan baru.
Sejak perang dunia 2 berakhir, bahaya ekspansi dari negara lain mulai mengecil. Konsepsi geopolitik pun segera berubah. Konsep geopolitik kita yang selama ini cenderung defensif dan lebih memusatkan perhatian pada pertahanan kedaulatan dari serangan luar, harus digeser menjadi aktivitas kreatif yang mampu memaksimalkan potensi laut untuk kesejahteraan. Laut harus dilihat sebagai peluang dan potensi ketimbang rintangan. Memadukannya terhadap wawasan nusantara yang kita miliki.
Geopolitik modern tidak lagi memfokuskan dirinya pada strategi perluasan kekuasaan dan kolonisasi wilayah, melainkan kemajuan teknologi. Urusan politik-keamanan bergeser menjadi soal ekonomi dan budaya. Dan dua bidang ini pun masih begitu sulit bagi indonesia untuk menjadi bermain peran besar dalam lanskap global.
Sepertinya tidak ada pilihan lain selain memanfaatkan segala potensi yang kita punya. Misalnya, melalui upaya rekonstruksi dan revitalisasi potensi bahari yang kita miliki. Kenapa bahari? Karena laut adalah keunggulan komparatif yang nyata-nyata kita miliki dibanding bangsa lain di dunia. Bangsa lain yang bukan bangsa Bahari mampu mengoptimalkan potensi lautnya, dan mengoptimalkan potensi sejarah juga potensi geografis kehidupan bahari kita.
Beruntung kita punya jejak sejarah panjang kehidupan bahari yang terekam dengan baik dalam wujud Jalur Rempah. Jalur Rempah adalah bukti peran besar bangsa kita sebagai bangsa bahari dalam jalur perdagangan dunia yang sangat berpengaruh pada berjalannya masa depan dunia. Perdagangan rempah ini pula yang telah menghubungkan dunia dari berbagai penjuru mata angin. Yang memiliki pengaruh besar terhadap revolusi teknologi pelayaran dan perdagangan ketimbang Jalur Sutra atau jalur lainnya. Kemajuan dunia pelayaran dan perdagangan tak mungkin dipicu hanya oleh upaya mencari Sutra dan Emas. Sutra dan Emas bukan kebutuhan primer. Rempah, dalam posisi ini, lebih dibutuhkan untuk kuliner, obat-obatan, kosmetik, pengawet, dan terbukti telah merevolusi cara hidup, bahkan menciptakan Kolonialisme dan Imperialisme yang mengubah peta geopolitik dunia.
Rekonstruksi dan revitalisasi potensi bahari bisa dikatakan sejalan dengan upaya rekonstruksi dan revitalisasi Jalur Rempah. Dari aspek sejarah, geografi, ekonomi dan budaya yang sangat kuat berkelindan dalam konsep Jalur Rempah.
Salah satunya adalah diproduksi pengetahuan mengenai peran-peran orang Nusantara, fakta sejarah, hingga imajinasi untuk berbagai kalangan. Untuk imajinasi ini, Paul Ricoeur membagi menjadi dua tingkatan: Pertama, Imajinasi reproduktif (Reproductive Imagination), yaitu imajinasi yang dibangun dengan cara menghadirkan kembali kenangan-kenangan dan kejayaan masa lalu. Yang Kedua, disebut sebagai imajinasi produktif (Productive Imagination), yaitu imajinasi kreatif yang menghadirkan gambaran tentang masa depan, yang belum pernah ada dan belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Imajinasi tingkat pertama bisa dikatakan sebagai kebanggan kita pernah menjadi bangsa bahari. Romantisme masa lalu sering menjadi alasan kuat untuk sadar. Tapi imajinasi ini dengan segera kehilangan daya pikatnya. Lagu nenek moyangku seorang pelaut, tidak serta-merta membuat para cucunya ingin menjadi pelaut. Hanya sebatas membuat kita tahu akan asal-usul dan potensi serta bakat yang kita punya. Di saat imajinasi tingkat pertama mengalami penurunan efektivitas, imajinasi tingkat kedua yang disebut imajinasi produktif perlu dihadirkan. Itu sebabnya berbagai penelitian sejarah, arkeologi, dan antropologi tidak cukup berhenti pada kesimpulan “kita pernah” tapi harus dikembangkan menjadi “kita bisa”.
Membuktikan bahwa bangsa kita pernah berjaya di laut, tidak cukup untuk membangun kesadaran bahwa kita bisa dan perlu menguasai ilmu pelayaran saja. Imajinasi Produktif dibutuhkan saat kisah-kisah kebesaran masa lalu tidak mampu memberi jawaban dan harus diganti iming-iming tentang masa depan yang di dalamnya dihadirkan sebuah horizon of expectation. Janji-janji mesianistik tentang bangsa yang besar.
Tidak mudah memang mengubah dan membalik begitu saja budaya darat yang sudah kita hidupi selama bertahun-tahun. Dibutuhkan upaya konkret yang intinya menjadikan laut sebagai ruang budaya baru, basis produksi baru. Menjadikan laut sebagai basis produksi, akan mengubah suprastruktur kesadaran masyarakat dengan sendirinya.
Di sini dibutuhkan revitalisasi Jalur Rempah menjadi penting. Menghidupkan Jalur Rempah tentunya berkaitan dengan pemanfaatan geografis juga ekonomi, dari penanaman kembali berbagai jenis rempah yang menjadi produk unggulan, hingga pelabuhan-pelabuhan bersejarah yang diaktifkan kembali. Kapal-kapal bisa menjadi tulang punggung lalu lintas perdagangan antar pulau. Rempah yang berlimpah, diolah dan diproses menjadi produk berkualitas ekspor. Terus menerus berinovasi dengan rempah serta budidayanya.
Sejatinya, membangun kembali kejayaan Jalur Rempah adalah sebuah upaya jangka panjang yang terencana. Dengan segudang manfaat eksternalnya, kita juga memperbarui KeIndonesiaan kita yang melulu inferior, menjadi terus relevan dan kontekstual dengan kebutuhan zaman di tengah pusaran perubahan besar-besaran yang terjadi di dunia.
Jalur Rempah harus dilihat sebagai sebuah jalur budaya. Jalur yang dalam sejarahnya mengakibatkan berbagai interaksi budaya dari begitu banyak bangsa dunia, penyebaran agama, pendidikan, pertukaran ilmu pengetahuan, seni, bahasa, teknologi perkapalan, hingga kepentingan politik. Jalur inilah yang turut membangun budaya dan identitas Indonesia seperti sekarang ini–yang majemuk. Jalur Rempah juga menguatkan ikatan Indonesia sebagai bangsa dengan keanekaragaman budaya, tradisi, bahasa, agama, dan etnis. Dengan merekonstruksi dan merevitalisasi Jalur Rempah, artinya kita pun turut memperkuat ikatan Indonesia yang di hari-hari terakhir ini disibukkan oleh wacana-wacana intoleransi akibat menguatnya sentimen primordial.
Tentu sudah banyak usaha yang dilakukan untuk itu. Tapi sekali lagi, membangun budaya bahari melalui rekonstruksi dan revitalisasi Jalur Rempah adalah pilihan strategis sekaligus tantangan bangsa ke depan. Jatuh bangunnya bangsa akan bergantung pada kemampuan kita mengelola mengembangkan laut, dan itu artinya juga akan mempengaruhi sukses tidaknya mewujudkan mimpi Indonesia menjadi poros maritim dunia, melalui program Jalur Rempah. Karena budaya bahari adalah asal-usul kita dengan segala kemungkinan-kemungkinan dan peluang masa depan. Seperti yang telah kita baca sepanjang tulisan ini: Sesungguhnya, Jalur Rempah adalah masa lalu dan masa depan kita.
sumber: kemdikbud.go.id